Oleh:
Yusuf Abdullah, Ketua Umum HMI Komisariat Iqbal
Lingkungan hidup
merupakan kumpulan komponen yang ada dalam kesatuan ruang dan saling berkaitan.
Jika ada salah satu unsur yang kurang atau bahkan tidak ada, maka dapat
dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan dalam lingkungan tersebut. Menjadi
sebuah kewajiban bagi manusia untuk tetap mengupayakan roda keseimbangan yang
terdapat di dalam lingkungan tersebut.
Berdasarkan data
yang dikeluarkan Worldmeters, manusia merupakan makhluk hidup yang mendominasi
bumi dengan total jumlah keseluruhan 7,7 miliar jiwa. Dengan jumlah angka yang
demikian, kehidupan manusia sangat bergantung sekali pada lingkungan hidup.
Dengan adanya permasalah dalam lingkungan hidup, akan sangat berdampak pada
kualitas kehidupan yang terdapat di dalamnya, termasuk salah satunya adalah
manusia.
Permasalahan yang
terjadi di dalam lingkungan, tidak semerta-merta ada dengan sendirinya. Secara
garis besar, permasalahan lingkungan terjadi akibat dari bencana alam,
pencemaran dan pengrusakan yang dilakukan manusia. Hal tersebut dilakukan oleh
manusia, tidak sedikit yang mencoba mengekploitasi keuntungan sebesar-besarnya.
Sehingga sering kali lingkungan menjadi
korban dari perbuatan tersebut.
Berdasarkan catatan
sejarah, awal mula pengeloalaan
lingkungan pertama kali terjadi pada era Neolitikum atau zaman Batu
Baru. Kala itu, manusia sudah mengenal tradisi berburu dan bercocok tanam,
meski dengan lahan garapan seadanya. Hingga kurun waktu tertentu, bercocok
tanam mereka rasa lebih menjanjikan. Alhasil aktivitas keseharian yang semula
mereka habiskan untuk berburu, selanjutnya mereka alihkan untuk perluasan lahan
agar bisa bercocok tanam dengan hasil yang lebih besar. Nah, dari sinilah
tonggak awal bercocok tanam dengan membuka lahan terlebih dahulu dimulai dan
berlangsung hingga sekarang ini.
Secara umum,
permasalahan lingkungan dibagi menjadi beberapa bagian, tiga bagian di
antaranya: polusi udara, deforestasi, dan limbah sampah yang menggunung. Data yang dirilis
greenpeace.org, pada tahun 2018 Jakarta mendapatkan peringkat sepuluh besar
sebagai ibu kota negara dengan kualitas udara terburuk sedunia. Jumlah
konsentrasi rata-rata tahunan PM2.5 di Jakarta pada tahun 2018 sangat buruk,
Jakarta Selatan mencapai 42.2 µg/m3 dan Jakarta Pusat mencapai 37.5 µg/m3. Jumlah
konsentrasi udara tersebut telah melebihi standar udara yang ditetapkan standar
nasional pada PP No. 41 Th 1999 tentang Pengendalian Udara, yaitu 15 µg/m3.
Hal ini menjadi
semakin parah, karena manfaat dan fungsi hutan sebagai paru-paru bumi sudah mulai
memprihatinkan. Kebakaran dan pengalihfungsian hutan yang kurang tepat menjadi
faktor terbesar atas hilangnya paru-paru bumi. Menurut data yang dirilis World
Wide Fund for Nature (WWF) berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik
Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut
setiap tahunnya. Hutan yang tersisa di Indonesia saat ini sekitar 130 juta
hektar, 42 juta hektar sudah habis ditebang.
Kemudian, jumlah
limbah sampah yang menggunung turut memperparah kondisi lingkungan hidup saat
ini.
Berdasarkan data yang dirilis BPS pada tahun 2016, jumlah tumpukan sampah
di Indonesia mencapai sekitar 65 juta ton pertahun. Hal tersebut diperparah
dengan pengelolaan sampah di Indonesia temasuk kategori terburuk kedua setelah Tiongkok.
Dari gambaran
problem di atas, masih belum cukup untuk menggambarkan permasalahan lingkungan
hidup saat ini. Namun, setidaknya gambaran di atas cukup mewakili permasalahan
lingkungan yang cukup mengkhawatirkan yang terjadi saat ini. Sehingga perlu
adanya upaya-upaya untuk menanggulangi masalah tersebut.
Kekeliruan
dalam berpikir
Permasalahan-permasalahan
lingkungan di atas muncul akibat dari pola pikir yang keliru. Pola pokir yang
dipahami kebanyakan masyarakat adalah adanya dikotomi antara manusia dengan
lingkungan. Sehingga berakibat pada nilai yang dipahami masyarakat bahwa
manusia sebagai nilai tertinggi dalam berkehidupan. Pusat dari berkehidupan
adalah manusia dan sesuatu yang selain manusia adalah hak bagi manusia untuk
menguasainya. Dengan adanya konsepsi ini, muncullah istilah antroposentris.
Cara berpikir yang
demikian, memunculkan egoisme pada manusia. Etika manusia terhadap segala
sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi sirna. Segala perbuatan manusia akan
selalu dianggap menjadi sebuah kebenaran, bahkan sekalipun itu salah. Hal ini
akan membuat kondisi lingkungan menjadi semakin memprihatinkan.
Dalam perkembangan
pola pikir tersebut, mendapat pertentangan dari sebagian masyarakat, karena hal
tersebut hanya akan terus membuat lingkungan semakin memprihatinkan. Maka,
muncullah pola pikir yang menjadi antitesis dari antroposentris. Pola pikir itu
bisa disebut ekosentris. Ekosentris menempatkan manusia dan lingkungan menjadi
kesatuan ekosistem. Artinya, ekosentris mencoba menghilangkan hierarki yang
dikonsepsikan antroposentris dengan memandang seluruh unsur yang ada di alam
saling bergantung sama lain.
Pola pikir
ekosentris menjadi solusi yang cukup tepat, karena pola pikir menjadi hal yang
fundamental untuk dibenahi. Pada kesempatan kali ini, penulis mengajak seluruh
pembaca untuk turut mengkampanyekan ekosentris sebagai solusi dari permasalahan
lingkungan. Wallahu a'lam bi al-shawwab.













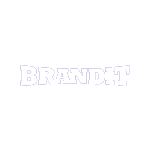



0 Komentar