Oleh: Muhammad Nabil Muallif
Nama saya Muhammad Nabil Muallif. Saya terlahir dari orangtua yang biasa-biasa saja. Ayah hanya seorang pegawai negeri sipil dan ibu hanya seorang guru honorer. Secara keilmuan, bapak pun hanya sarjana manajemen lulusan Universitas Borubudur. Sedangkan ibu, beliau hanya seorang sarjana psikologi lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena itu, tradisi keilmuan dalam keluarga saya bisa dikatakan masih begitu kurang. Ditambah, ayah merupakan seorang muallaf yang masih perlu mempelajari dasar-dasar agama. Jadi, saat saya kecil, bukan ayah yang mengajarkan agama kepada anak-anaknya seperti orangtua kebanyakan, akan tetapi ibu lah yang mengajari. Itu pun hanya sekedar pembiasaan membaca Al-Qur’an setelah maghrib. Yang lain, saya dapatkan saat jenjang SD sampai SMA. Hal itu lah yang menantang saya agar bisa melahirkan tradisi keilmuan yang luas pada anak dan cucu saya kelak, terutama dalam hal agama. Meski begitu, ayah dan ibu merupakan seorang yang sangat ulet. Saya bersyukur mempunyai orang tua yang mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Terutama dalam hal gizi dan pendidikan.
Di keluarga besar saya, belum ada satu pun orang yang pernah hafal Al-Qur’an. Mayoritas mereka bergelut pada bidang-bidang profesional. Hal itu lah yang membakar semangat saya untuk menghafal Al-Qur’an saat kelas 11. Walaupun, metode yang saya gunakan salah kaprah saat saya bandingkan dengan metode yang Abah Nasih ajarkan. Tapi, semangat itu ada. Saya rela bermalam di masjid pondok setiap hari untuk menambah target hafalan. Bahkan, ketika ada mata pelajaran yang saya rasa membosankan, saya lebih memilih berdiam diri di masjid untuk menghafal Al-Qur’an daripada mengikuti pelajaran tersebut. Perjuangan menghafal berlanjut hingga kelas 12. Semangat saya bertambah dua kali lipat ketika itu. Sebab, saat wisuda kelulusan, bagi santri yang berhasil menyetorkan hafalan Al-Qur’an 30 juz dengan syarat minimal menyetorkan setengah juz hafalan sekali duduk, maka akan ada reward dari pondok berupa uang sebedar 2,5 juta dan selendang yang bertuliskan *Al-Hafidz*. Tapi, saya sadar. Hafalan saya hanya sekedar lewat saja. Butuh waktu lagi untuk memperbaiki hal tersebut.
Setelah lulus SMA, Mbah Rohmat (kakek saya dari ibu) menggadang-gadang saya sebagai orang yang akan meneruskan pondok yang telah beliau rintis. Alasannya karena di antara anak-anak dan cucunya, hanya saya yang mengambil jurusan keagamaan. Saat itu pula, saya mempunyai keinginan untuk bisa melanjutkan studi S1 keagamaan di Timur Tengah (Sebelum Abah Nasih mengubah pemikiran saya tentang paradigma pendidikan Islam yang ada di Timur Tengah). Jadi, sinkron antara impian saya dengan harapan Mbah Rohmat. Untuk memudahkan saya untuk kuliah di Timur Tengah kelak, Mbah Uti dan ibu menyarankan saya agar mendalami bahasa Arab terlebih dahulu bersama Om Nasih sembari menunggu pengumuman kelulusan Univesitas Islam Madinah, pesan beliau berdua. Saya pun mengiyakan. Singkat cerita, saya pun mondok di tempat yang sangat mempengaruhi perubahan pemikiran dan karakter pribadi saya saat ini. Tempat tersebut ialah Monash Institute.
Namun, takdir berkata lain. Impian untuk mengeyam pendidikan di Universitas Islam Madinah harus kandas. Ya, saya tidak diterima di universitas tersebut. Anehnya, tidak ada satu pun rasa kecewa dan putus asa. Semua rasa itu sudah terlebih dahulu digantikan oleh doktrin Abah Nasih yang mengatakan bahwa kuliah di mana pun itu sama saja. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri, tidak ada universitas yang benar-benar menjamin kualitas seseorang. Perbedaannya hanya pada legitimasi dan kelebihan pada kemampuan berbahasa saja.
Doktrin itu terbukti. Sesekali saya berdiskusi dengan salah satu teman yang melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar, Mesir. Saya bertanya terkait perkembangan apa saja yang sudah ia dapatkan selama menjalani studi hampir dua tahun di Mesir. Jawabannya mencengangkan. Selama dua tahun, ia masih kebingungan dalam aspek-aspek dasar nahwu dan shorof. Kemudian, saya tantang untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab kepada saya. Katanya, belum lancar. Sebab, selama ini, ia hanya bergaul dengan teman-teman yang berasal dari Indonesia saja, alasannya. Semenjak itu, saya semakin yakin dengan doktrin yang selalu Abah ajarkan. Termasuk hal tadi juga membuktikan doktrin tentang pentingnya menguasai ilmu alat. Seperti yang pernah Abah analogikan, bahwa seseorang yang belajar agama Islam namun tidak menguasai ilmu alat itu laksana nelayan yang mencari ikan di laut tanpa memiliki alat pancing. Selamanya ia tidak akan pernah mendapatkan ikan tersebut. Begitu pula orang yang mencari ilmu, selamanya tidak akan pernah mendapatkan ilmu tersebut. Lama kelamaan akan lelah, lalu berhenti dan menyerah.
Di Monash Institute, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang selalu diajarkan oleh Abah Nasih dan Bang Aziz, serta senior-senior yang lain. Mulai dari visi membangun jamaah, penguasaan khazanah keislamaan, perubahan cara berpikir dan berperilaku, dan logika kepemimpinan. Saya merasakan semua yang diajarkan di Monash Institute sangat berguna sebagai bekal buat masa depan saya, yang nanti akan melanjutkan estafet perjuangan Mbah Rohmat dalam membangun pondok pesantren. Tak hanya itu, saya terus belajar untuk meningkatkan kepercayaan diri yang dibarengi dengan kompetensi. Yang menjadi motivasi saya ialah, berkebalikan dengan kata-kata Anas Urbaningrum, bisa dikatakan saya adalah bayi lahir yang diharapkan oleh Mbah Rohmat. Tentu, saya tidak bermaksud mengklaim bahwa diri saya dibutuhkan, akan tetapi perkataan tadi selalu menjadi pecut bagi saya untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Menjadi pemimpin ideal adalah dambaan bagi saya. Bekalnya adalah hafal dan paham Al-Qur’an sebagai ideologi, bisa menulis sebagai alat publikasi, dan mempunyai uang yang sangat banyak untuk mempermudah segala hal. Tiga komponen tadi saya lakukan secara bersamaan saat ini. Meskipun, saat ini masih sangat jauh dari kata berhasil. Saya yakin dan percaya, suatu saat, berkat pertolongan Allah dan usaha yang ekstra maksimal serta konsisten, saya akan memetik hasilnya kelak. 2,5 tahun kesempatan yang tersisa akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Bismillah.
*Ditulis pada malam hari, setelah Abah menginstruksikan seluruh disciples untuk menuliskan momentum apa yang didapatkan untuk menghafalkan Al-Qur’an.









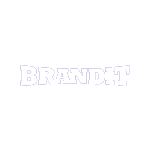







0 Komentar